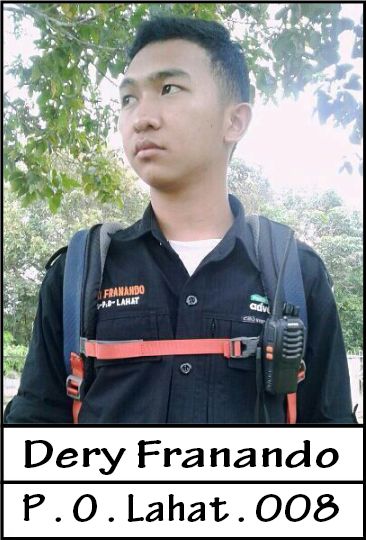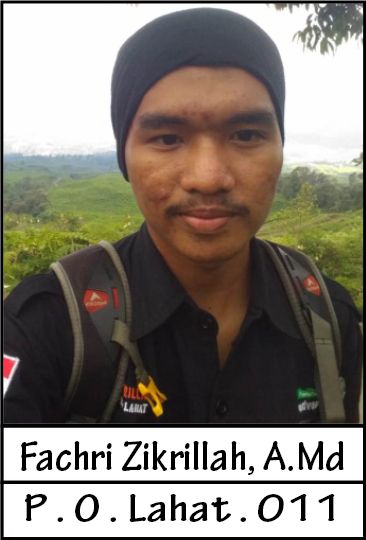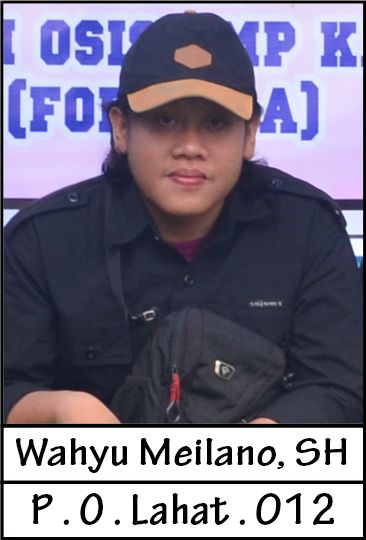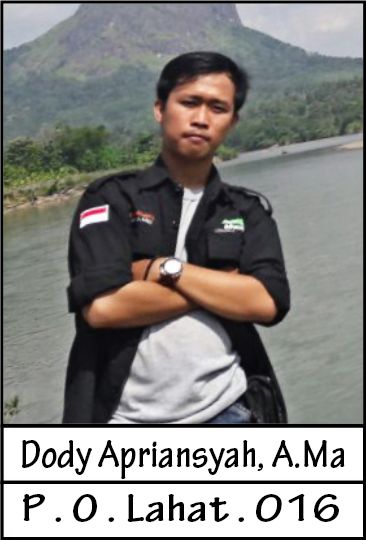Imperium Sriwijaya nyaris terlupakan
dari sejarah Nusantara. Kebesarannya sempat terhapus . Adalah peneliti asal
Perancis George Coedes yang berjasa mengungkapkan kembali kejayaannya melalui
penelitiannya tahun 1918.
Coedes berhasil menemukan kode kuncinya
lewat kata “San-fo-ts’i’’ yang banyak tercantum dalam naskah-naskah Cina,
seperti laporan perjalanan I Tsing, pengelana besar dari Tiongkok abad ke-7 M.
Sebelumnya “San-fo-ts’I” dibaca sebagai “Sribhoja”, yang merujuk pada satu
kerajaan Melayu tua yang tak jelas riwayatnya. Coedes untuk kali pertama
membaca kata-kata Cina itu sebagai Sriwijaya. Bahkan, berdasar telaahnya atas
Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka 1898, Coedes mengidentifikasi bahwa Kedatuan (istana) Sriwijaja
ada di Kota Palembang. Teori Coedes itu makin tak terbantahkan
dengan penemuan prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo di Palembang di tahun
1920.
Lokasi Kedatuan Sriwijaya diperkirakan
ada di antara Bukit Siguntang dan Sabokingking, Palembang. Embrio Sriwijaya
telah tumbuh sejak awal abad ke-6 di Palembang. Namun, Kebesaran Sriwijaya
setidaknya mulai terpancar tahun 671, ketika I-tsing berkunjung ke ibukota
negeri maritim itu yang bertahta di sana saat itu adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Prasasti Bukit Kapur menyebutkan bahwa sang prabu berhasil menaklukkan Kerajaan Menanga
di Tanah Melayu, Taruma Negara (Sunda), dan Kalinga (Jawa). Raja berikutnya, Sri
Indrawarman, punya visi diplomatik yang canggih. Ia mengirimkan utusan ke
Kaisar China di Beijing, juga kepada Khalifah Ummayah I di Damaskus. Sang raja
ingin menjalin hubungan yang bersahabat. Begitu halnya dengan Rudra Vikraman,
yang naik tahta tahun 728, tetap menjalin hubungan dengan Cina. Tradisi itu
berlanjut hingga Sriwijaya runtuh. Sejak era Dapunta Hyang Sri Jayanasa,
Sriwijaya sudah menguasai jalur perdagangan regional. Kerajaan maritim ini
mengontrol Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata dan Laut Jawa.
Pada masa kejayaannya, Sriwijaya
mendominasi Asia Tenggara, dan menguasai wilayah Thailand Selatan hingga
Kamboja. Sejarah juga mencatat bahwa Sriwijaya sempat mengirim ekspedisi
menyeberangi samudera hingga ke Madagaskar. Penguasa Sriwijaya adalah pemeluk
Budha. Mereka sering disebut Wangsa Syailendra. Namun, sejak tahun 743 hingga
835, kekuasaan di Kedatuan Palembang kosong. Para sejarawan menafsirkan bahwa k
Namun, dalam perkembangannya, pamor Sriwijaya berangsur surut. Serbuan Rajendra Cola Dewa, Raja Cola dari Tamil, India, membuat Sriwijaya ambruk tahun 1025. Raja Cola tak menduduki kedatuan Sriwijaya, dan tidak pula menempatkan wakilnya di sana. Targetnya sebatas untuk mengakhiri hegemoni Sriwijaya di Selat Malaka pun tercapai. Serangan tentara Tamil itu membuat Sriwijaya sulit bangkit. Dalam situasi ini muncul kekuatan baru, Kerajaan Dharmasraya di Jambi, yang berkedudukan di tepian Sungai Batanghari. Kedatuan Melayu ini dikuasai oleh Wangsa Mauli . Menjelang akhir abad 12 M, Kedatuan Sriwijaya yang sudah berganti nama menjadi Palembang menjadi negeri bawahan Jambi. Sejarah terus bergerak. Hegemoni Dharmasraya tergeser oleh kekuatan baru dari Jawa. Palembang jatuh di bawah pengaruh Singasari 1283, dan kemudian berpindah tangan ke imperium maritim Jawa berikutnya, yakni Majapahit. Tak mau berada di bawah panji Majapahit, Sang Nila Utama, Raja terakhir Sriwijaya, memilih hijrah ke Pulau Bintan dan membangun kekuatan di sana. Setelah cukup kuat, Sang Nila pun menyerang Tumasik (Singapura), dan menyingkirkan Tumagi, “gubernur” yang mewakili Kerajaan Ayuttha dari Thailand. Penerus wangsa Sriwijaya ini bertahan hingga empat generasi, sampai kemudian Sang Parameswara, cicit dari Raja Sang Nila Utama, memindahkan kekuasaannya ke Malaka, di Semenanjung Malaya pada tahun 1402, menghindari gesekan dengan Majapahit. Ketika itu di pesisir Timur Aceh itu telah tumbuh pula kekuatan baru : Kerajaan Islam Samudera Pasai. Prameswara memilih berdamai dengan Pasai. Ia pun memeluk Islam, menyunting salah satu puteri Raja Pasai, lantas menobatkan dirinya sebagai Sultan Iskandar Syah. Palembang sendiri tetap menjadi bandar yang hidup. Namun, Majapahit ternyata tak mengelola Palembang dengan sungguh-sungguh sehingga kota ini sempat pula jatuh ke tangan pendatang Cina di bawah pimpinan Chen Tsu-I di tahun 1370. Chen adalah saudagar kaya dari Guangzhou yang lari ke Palembang karena urusan politik. Dengan kekuatan harta dan laskarnya, Cheng menjadi penguasa Palembang, dan ia mencoba mengontrol Selat Malaka dengan armada lautnya. Aksi kekerasan oleh kaki tangannya membuat Chen dikenal sebagai bos perompak Cina yang berpangkalan di Palembang. Adalah ekspedisi Cheng Ho 1407 yang mengakhiri petualangan Chen Tsu-I. Kekuatan militernya dihancurkan dan Chen diboyong pulang ke Cina untuk menjalani hukuman mati. Cheng Ho mengangkat salah satu anak Chen sebagai kepala perwakilan dagang resmi Kerajaan Cina di Palembang. Situasi beranjak aman. Dalam kevakuman ini lahir penguasa baru di Palembang dan dikenal sebagai Sultan Mugni. Ia memimpin daerah yang plural. Di sana ada komunitas Melayu, Jawa, Cina, dan dalam jumlah terbatas ada pula orang Arab dan India. Namun, Majapahit tak melepas klaimnya atas Palembang. Setelah kemelut internnya mereda, Raja Brawijaya Kertabumi mengirim Arya Damar ke Palembang sebagai raja muda (adipati) tahun 1445. Untuk menghindari ketegangan, Arya Damar menempuh jalan damai. Ia mendekati Sultan Mugni, memeluk Islam, bahkan menyunting Puteri Semindung Biduk, anak kesayangan Sang Sultan. Berikutnya, Sultan Mugni yang telah berusia lanjut mengangkat Arya Damar menjadi penguasa Palembang. Ia berganti nama menjadi Arya Dilah (dari kata Andillah). Ia dipercaya mengasuh Raden Fatah, salah satu putera rajaMajapahit, di Palembang dan menjadikannya sebagai Muslim. Dari jauh, Arya Dillah menyaksikan pamor Majapahit memudar. Sebelum runtuh, Arya Damar mengirim Raden Fatah pulang ke Jawa. Atas seizin Raja, R. Fatah membangun kota di Demak, Jawa Tengah. Akhirnya, suratan nasib membawa Raden Fatah menjadi penguasa Jawa setelah Majapahit ambruk. Ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Syeh Akbar Al Fatah, dan bertahta di Keraton Demak Bintoro 1500-1518. Klaim atas Palembang tidak pernah ia lepaskan. Ia berniat mengirim puteranya Pati Unus ke Palembang sebagai adipati, namun sang pangeran gugur dalam misi penyerbuan ke Malaka, memerangi kolonialis Portugis. Sepeninggal Arya Damar, Palembang dipimpin oleh Karang Widara. Kekuasaan Demak berlangsung singkat saja dan berujung perang suksesi antara Arya Penangsang (penguasa Jipang) dan Hadiwijaya (penguasa Pajang). Arya Penangsang terbunuh. Hadiwijaya membangun kekuasaan yang sinkretis di Pajang — dan berlanjut ke Mataram. Sejumlah pengikut Arya Penangsang menyingkir ke Palembang. Mereka membangun kerajaan Islam di situ.
Kesultanan Palembang
Penguasa pertama di situ adalah Ki Gede
Ing Suro. Ia mendarat di Palembang 1552. Setelah 17 tahun berkuasa, ia
digantikan keponakannya karena tak punya anak lelaki. Penguasa baru ini juga
bergelar Ki Gede Ing Suro. Dinasti Suro membangun keraton di suatu lokasi yang
kini dikenal sebagai Kuto Gawang. Selama berkuasa di Palembang hingga 1823,
Dinasti Suro itu meninggalkan empat situs keraton, yakni Kuta Gawang, Beringin
Janggut, Kuta Tengkuruk, dan situs Kuta Besak yang hingga kini masih utuh,
terletak di jantung kota Palembang Pengaruh tradisi keraton Jawa masih melekat
pada Dinasti Suro. Kerajaan Palembang juga menjalin hubungan baik dengan
Kerajaan Mataram di Jawa. Maka, nama-nama penguasa Palembang pun masih berbau
Jawa seperti Ki Mas Adipati, Pangeran Madi Alit, atau Pangeran Seda Ing Pura.
Namun, dalam perjalannya Kerajaan Palembang melepas identitas kejawaannya,
seraya mendeklarasikan sebagai kerajaan Islam pada tahun 1675 dengan nama
Kesultanan Palembang Darussalam. Keengganan Mataram membantu Palembang
memerangi Belanda turut mempercepat proses ini. Deklarasi Kesultanan Palembang
dilakukan Sri Susuhunan Aburahman Cinde Walang yang bertahta antara 1659-1706.
Para penerus tahtanya kemudian hari menyandang gelar sultan dengan nama Islam
di belakangnya. Pengaruh budaya Arab dan Melayu menguat. Pada masa kejayaannya,
kekuasaan Kesultanan Palembang juga hadir di pedalaman, bahkan hingga Lubuk
Linggau. Di sana ada kepala daerah yang bergelar Dipati, yang membawahi para
kepala adat yang disebut pasirah. Hubungan pusat dan
pedalaman dilalukan melalui jalur sungai. Kesultanan Palembang pun memiliki
aturan baku untuk tata pemerintahannya, yang tertuang dalamKitab Simbur Cahaya, yang ditulis dalam
Bahasa Melayu di era pemerintahan Ratu Sinuhun 1639-1650. Dalam perjalanannya Simbur Cahaya ini mengalami
beberapa kali perubahan sesuai perkembangan zaman. Pada edisi terakhir yang
terbit abad 19, Simbur Cahaya telah mengatur pula tentang proses perkawinan yang lebih murah.
Sultan-sultan Palembang ini umumnya enggan berkolaborasi dengan Belanda maupun
Inggris. Gerak para pedagang asing dari Arab, Cina dan India amat dibatasi,
termasuk perusahaan Belanda dan Inggris yang datang dengan membawa pengawal
bersenjata. Orang asing hanya diijinkan menggelar usaha dan bermukim di
Seberang Ulu. Kawasan Ilir hanya untuk keluarga istana, pangeran, bangsawan,
mantri (punggawa yang hanya diangkat oleh sultan), dan penduduk yang terikat
hubungan patron-klien dengan para bangsawan. Kalau pun ada pengecualian, hanya
berlaku bagi orang Arab yang menjadi guru spiritual keluarga istana (umumnya
orang Arab), dan orang Arab serta Cina yang diangkat sultan sebagai mantri.
Sikap keras Kesultanan Palembang itu menciptakan ketegangan dengan kaum
kolonial Belanda. Konflik bersenjata beberapa kali terjadi. Sultan Mahmud
Badaruddin II (1767-1852) melanjutkan tradisi dinastinya yang tak mau tunduk
dengan kekuatan kolonial Barat. Ia menyelesaikan bangunan benteng besar dengan
tembok setebal 1,9 meter, yang dirintis pendahulunya, untuk melawan kekuatan
kolonial Barat. Bangunan besar itu kini dikenal sebagai Benteng Kuto Besak yang
di pusat kota Palembang. Perang terbuka pun pecah. Setelah tiga kali melakukan
serangan, serdadu Belanda akhirnya menundukkan tentara Palembang. Sultan
diasingkan ke Bandaneira (Maluku) dan kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam
dihapus sejak 1823. Selanjutnya, Sumatera Selatan sepenuhnya di bawah kendali
Residen Belanda yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal.
Era Baru
Kehadiran Pemerintah Kolonial Hindia
Belanda itu sontak mengubah struktur sosial di Palembang. Pengaruh para
bangsawan merosot setelah mereka kehilangan hak-hak istimewa atas tanah
pertanian, perniagaan, dan cukai. Sebagian besar mereka jatuh miskin, uang
tunjangan yang diberikan pemerintah kolonial sebagai kompensasi atas
penghapusan hak-hak istiwewa sama sekali tidak memadai. Tatanan berubah total. Di Palembang muncul kelas menengah baru,
yakni para saudagar Arab dan Tionghoa. Mereka menggantikan posisi para priayi.
Runtuhnya Kesultanan membuat saudagar Arab dan Cina lebih leluasa memilih tempat tinggal. Rumah-rumah mereka tersebar
di banyak kampung dengan bentuk bangunan mentereng dan dibuat dengan kayu-kayu
nomor satu. Beberapa dari mereka membangun rumah tembok, hal yang ditabukan di
zaman Kasultanan Palembang. Penduduk pribumi yang sukses secara ekonomi juga
ikut mendobrak adat lama itu dengan membangun rumah-rumah yang mentereng. Dalam
mengelola pemerintahan, Kolonial Belanda masih memanfaatkan struktur lama,
dengan pasirah yang memimpin marganya di dusun masing-masing. Di atas mereka ada
demang yang berada di bawah pengawasan kontrolir Belanda. Selanjutnya para
kontrolir bertanggung jawab kepada residen. Dalam kepemimpinan marga ini,
pasirah didampingi khatib dan lebai yang otoritasnya di bersandar pada tradisi Islam. Dengan makin
terbukanya wilayah ini, Karesidenan Palembang pun dibagi menjadi 9afdeeling (semacam kabupaten di Jawa). Namun, berbeda dari pola Jawa,
afdeeling Palembang tak memerlukan pejabat tradisional setingkat bupati.
Afdeeling di daerah Palembang hanya dipimpin oleh pejabat kolonial dengan
predikat Asisten Residen, yang ke atas bertanggung jawab pada residen, dan ke
bawah memimpin sejumlah kontrolir.Tradisi Islam menjadi unsur penting dalam
tatanan masyarakat Sumatera Selatan, baik di Kota Palembang maupun
didaerah pedalaman ilir dan ulu. Maka Pemerintah Hindia Belanda perlu mengangkat Pangeran Penghulu (dari keluarga
Sultan) sebagai pejabat pemangkuadat. Ia menyeleksi dan menyesahkan khatib serta lebai yang antara lain bertugas memudahkan pernikahan. Mahalnya biaya nikah dianggap
menjadi pangkal rendahnya pertumbuhan penduduk. Ketika Sultan Mahmud Badaruddin
II bertahta di awal abad 19, penduduk Kesultanan Palembang diperkiran baru
sekitar 300.000 jiwa. Pemerintah Hindia Belanda tak banyak
membuka investasi di Karesidenan Palembang hampir di
sepanjang abad 19. Kehadirannya lebih untuk mengamankan pertambangan timah di
Bangka yang kemudian melebar ke Belitung. Perhatiannya atas wilayah di
luar Jawa relatif tidak terlalu besar sampai menjelang pergantian abad 19 ke
20. Investasi pemerintah ketika itu diarahkan ke pengembangan infrastruktur
ekonomi di Jawa yang mengalami booming pasca pemberlakukan kebijakan tanam paksa (cultuur stelsel). Perekonomian
Karesidenan Palembang mulai menggeliat dengan tumbuhnya industri minyak.
Eksplorasi produksi dimotori oleh perusahaan swasta Nederlandsche Indische Exploratie Maatschappij tahun 1895, yang mengelola ladang di daerah Banyuasin dan Jambi.
Dengan makin meluas areal konsesi di tangannya, swata ini pun menggandeng
perusahaan negara NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij atau Royal Dutch Petroleum , membentuk kongsiSumatera–Palembang Petroleum Maatschappij. Selain memproduksi
minyak mentah, kongsian ini membangun kilang mini di Bayung Lincir. Sementara
itu ladang-ladang minyak di Lematang Ilir dan Muara Enim dikelola oleh Muara Enim PetroleumMaatschappij. Ladang-ladang minyak baru kemudian ditemukan beberapa tempat.
Jalan-jalan darat pun dibangun menuju ke depot-depot minyak mentah itu. Dengan
meruahnya minyak mentah ini, dibangunlah sebuah kilang besar di Plaju, dan
kilang itu mulai beroperasi tahun 1900. Industri pengolahan minyak itu dikelola
oleh perusahan patunganRoyal Dutch dan Shell, perusahaan swasta Belanda yang di
kemudian hari tumbuh sebagai raksasa minyak dunia. Kilang Plaju saja tidak
cukup. Maka, Stanvac membuka kilang baru di Sungai Gerong, 1926. Booming minyak itu kemudian
mendorong Pemerintah Hindia Belanda membangun Palembang menjadi kota modern di
awal abad 20. Kebun karet yang kini menjadi komoditas unggulan di Sumsel juga
baru muncul awal abad 20, tidak lama setelah tanaman bergetah itu dibudidayakan
di Sumatera Timur 1902. Perkebunan lalu menjamur memanfaatkan bekas lahan
perkebunan tembakau yang telah gagal secara bisnis. Rakyat tidak mau
ketinggalan. Mereka menanamnya untuk mengisi sebagian lahannya yang diusahakan
secara berpindah-pindah itu, dan ternyata hasilnya bagus. Tumbuhlah perkebunan
rakyat di Karesidenan Palembang. Kelapa sawit sebetulnya hadir dulu di Sumsel.
Namun, uji coba budidayanya gagal memberikan hasil yang memadai. Maka, setelah
minyak bumi dan karet, komoditas andalan Sumsel di permukaan abad 20 adalah
batu bara yang mulai digali 1918 dari Tanjung Enim. Bersama dengan kopi, yang
telah dibudidayakan secara terbatas di daerah Lahat, Lubuk Linggau serta Pagar
Alam, minyak bumi, batu bara, dan karet adalah penggerak ekonomi Sumsel sejak
awal abad 20.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
pun mengantar Karesidenan Palembang sebagai bagian dari Negara Republik
Indonesia. Dalam perjalanannya, Karesidenan Palembang pun berubah status
menjadi Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai potensinya, Sumsel cepat tumbuh
menjadi sentra industri yang penting di Indonesia. Palembang muncul sebagai
kota utama, dan diperkuat dengan ikon khas Jembatan Ampera, yang ketika
diresmikan 1965, merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Industri
pengolahan minyak di Plaju terus tumbuh dan menjadi kilang utama nasional.
Pupuk Sriwijaya yang mulai beroperasi 1963 menjadi tonggak bagi lahirnya
industri petrokimia domestik. Karet hasil perkebunan besar dan kebunan rakyat
pun memasok bagian besar dari kebutuhan karet nasional. Bisnis hutan tanaman
industri (HTI) pun tumbuh secara masif sejak dekade 1990-an di Sumsel, hingga
membuat provinsi ini menjadi daerah yang penting bagi industri pulp dan kertas
nasional. Berbarengan dengan itu, tanaman kelapa sawit, yang diusahakan oleh
rakyat maupun perkebunan besar, semakin luas, dan melahirkan banyak industri di
hilir. Satu hal lagi yang sering luput dari perhatian, bahwa Sumsel adalah
produsen kopi terbesar di Indonesia. Kota-kota di Sumsel tumbuh menjadi kota
modern. Palembang lantas terlahir kembali sebagai bandar internasional. Bahkan,
sejak 2005 Pemerintah menetapkan ‘’Mahkota Rawa Palembang’’ sebagai Kota Wisata
Air. Palembang akan didorong untuk bersaing dengan Bangkok dan Phnompenh
sebagai kota yang mempesona dengan panorama airnya
 Home
Home